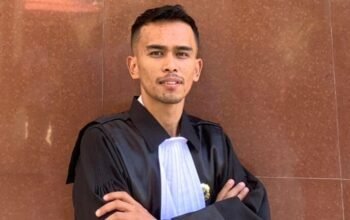Oleh :Fajar (Aktivis GAM Makassar)
Ketika Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta–Bandung pada Oktober 2023, banyak yang menyebutnya sebagai tonggak sejarah baru bagi modernisasi transportasi Indonesia. “Whoosh” singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat dipromosikan sebagai simbol kemajuan infrastruktur nasional, sekaligus bukti bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara maju. Namun dua tahun berlalu, euforia itu meredup. Proyek yang dulunya dijanjikan tanpa beban pada APBN kini justru menimbulkan tanya besar siapa yang menanggung utang yang membengkak hingga lebih dari seratus triliun rupiah?
Sejak awal, proyek ini sarat dengan muatan politik dan ambisi besar. Jokowi ingin meninggalkan jejak monumental melalui pembangunan infrastruktur berskala raksasa. Pilihan mitra akhirnya jatuh kepada Tiongkok setelah Jepang tersingkir, dengan janji manis bahwa proyek ini akan sepenuhnya berbasis business to business (B2B) tanpa jaminan dari pemerintah. Namun para ekonom dan mantan pejabat Kementerian Perhubungan saat itu telah mengingatkan bahwa jarak Jakarta–Bandung yang hanya sekitar 142 kilometer terlalu pendek untuk proyek kereta cepat berkecepatan 350 km/jam. Proyeksi jumlah penumpang dan tingkat keuntungan dinilai terlalu optimistis. Sayangnya, peringatan itu tenggelam di tengah euforia pembangunan dan dorongan politik untuk segera menuntaskan proyek prestisius ini.
Pelaksanaan proyek berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium gabungan antara BUMN Indonesia sebesar 60 persen dan perusahaan Tiongkok sebesar 40 persen. Mayoritas pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) yang mencakup sekitar 75 persen dari total biaya, sementara sisanya ditanggung oleh modal para pemegang saham. Masalah besar mulai muncul ketika biaya proyek membengkak atau dalam istilah teknis disebut cost overrun. Dari perkiraan awal sekitar Rp 80 triliun, biayanya kini melonjak hingga lebih dari Rp 114 triliun. Penyebabnya beragam, mulai dari revisi desain, pembebasan lahan yang berlarut, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah akhirnya menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI, langkah yang secara tidak langsung mematahkan janji awal “tanpa APBN”. Dari sinilah publik mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Secara ekonomi, proyek Whoosh kini menjadi paradoks pembangunan, di satu sisi mampu meningkatkan citra infrastruktur nasional dan menciptakan lapangan kerja namun di sisi lain belum menunjukkan kinerja finansial yang sehat.
Pendapatan dari penjualan tiket belum mampu menutup biaya operasional dan cicilan bunga pinjaman. Target penumpang 30–50 ribu orang per hari masih jauh dari harapan. Akibatnya, proyek ini belum layak secara bisnis. Situasi ini memunculkan istilah “bom waktu fiskal” karena bila operator tak mampu membayar utang, kemungkinan besar beban itu akan kembali ke negara. Pemerintah mungkin berulang kali menegaskan bahwa APBN tak terlibat. Tapi faktanya, BUMN sebagai pelaksana proyek tetap bergantung pada dukungan fiskal negara.
Secara politik, Whoosh adalah proyek warisan Jokowi. Ia bukan hanya simbol transportasi modern, tetapi juga representasi kemitraan strategis Indonesia–Tiongkok di bawah payung Belt and Road Initiative (BRI). Namun lambang kemajuan itu kini berubah menjadi beban politik bagi pemerintahan berikutnya. Proyek yang dulu dielu-elukan sebagai keberanian berinvestasi besar kini justru dipertanyakan dari sisi rasionalitas ekonominya. Desakan agar dilakukan audit menyeluruh semakin menguat di DPR, sementara publik menuntut transparansi terkait nilai pinjaman dan skema pelunasannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang Whoosh. Ia menolak menjadikan beban proyek ini sebagai tanggungan fiskal negara dan menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Danantara, holding investasi BUMN yang menaungi proyek tersebut. Sikap ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga jarak dari tanggungan finansial proyek warisan Jokowi, sekaligus langkah hati-hati agar beban keuangan negara tidak semakin berat.
Namun pernyataan itu juga menimbulkan pertanyaan baru, bila BUMN yang menanggung seluruh utang mengalami kesulitan likuiditas bukankah dampaknya tetap akan kembali ke APBN melalui berkurangnya dividen dan menurunnya kemampuan investasi negara? Dengan kata lain, sekalipun secara teknis utang itu tidak langsung ditanggung oleh negara, secara ekonomi efeknya tetap terasa pada keuangan publik.
Proyek Whoosh memberi pelajaran penting bahwa ambisi politik tidak selalu sejalan dengan perhitungan ekonomi. Dalam teori pembangunan, infrastruktur seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal, bukan sekadar demi kebanggaan nasional. Kita tentu mendukung pembangunan besar, tetapi yang dibutuhkan adalah pembangunan yang transparan, terukur dan berkelanjutan. Infrastruktur mestinya menjadi aset produktif, bukan warisan utang yang membebani generasi berikutnya.
Kini, proyek Whoosh menjadi cermin dari paradoks kebijakan publik di Indonesia, tarik-menarik antara ambisi politik, kalkulasi ekonomi dan tanggung jawab fiskal. Pemerintah boleh berbangga dengan kecepatan 350 kilometer per jam, tetapi publik menuntut kecepatan yang lain kecepatan dalam menjawab siapa yang akan bertanggung jawab atas utang yang membengkak. Sebab, pada akhirnya kecepatan yang paling dibutuhkan bangsa ini bukanlah pada rel kereta, melainkan dalam menegakkan transparansi, integritas dan akuntabilitas.