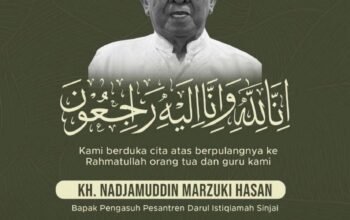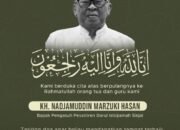Oleh : Muh. Afriansyah, S.H.,M.H.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto sertaabolisi kepada Thomas Trikasih Lembong menjadisorotan publik dan memicu berbagai respons.
Langkah ini menjadi momen signifikan dalam konteks hukumdan politik nasional, mengingat kedua instrumentersebut amnesti dan abolisi, merupakan kewenangankonstitusional yang jarang digunakan, namunberdampak luas. Lebih dari sekadar tindakanadministratif, keputusan tersebut memunculkandiskursus mengenai tujuan, moralitas, dan esensi daripenegakan hukum di tengah realitas kekuasaan yang dinamis.
Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, presiden memang memiliki otoritas untuk memberikanamnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaannya harus melalui mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari Dewan PerwakilanRakyat.
Dalam kasus ini, prosedur formal telah diikutidengan tertib Presiden mengajukan permintaan, DPR memberikan persetujuan, dan kemudian keputusanresmi dikeluarkan. Dari sudut pandang hukum positif, tidak terdapat pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku.
Meski demikian, hukum tidak hanya berbicaratentang legalitas prosedural, tetapi juga harusmempertimbangkan aspek etika, nilai, dan keadilan.Hal ini mengundang pertanyaan yang lebih mendalam.Apakah keputusan tersebut layak secara moral dalamsistem negara hukum.
Jika ditinjau melalui pendekatan utilitarianisme, kebijakan ini bisa dipandang sebagaiupaya untuk menjaga kestabilan politik nasional, meredam polarisasi, dan membuka ruang rekonsiliasi.Namun, apabila dianalisis melalui perspektif teorikeadilan John Rawls, maka kebijakan tersebut harusdiuji. Apakah keputusan itu benar-benar menjaminperlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, terutama bagi masyarakat yang menaruh harapanterhadap integritas sistem hukum yang bebas daripengaruh kekuasaan politik.
Realitas bahwa tokoh-tokoh yang menerimapengampunan merupakan individu yang terlibat dalamkasus korupsi dan memiliki afiliasi politik kuatmembuat keputusan ini sarat dengan konsekuensimoral. Di satu sisi, publik melihat ini sebagai bentukpengampunan negara. Namun di sisi lain, munculkekhawatiran akan terjadinya delegitimasi terhadaplembaga peradilan, khususnya terhadap kerja keraspenegak hukum yang telah menempuh proses panjanguntuk membawa perkara ini ke meja hijau.
Kritik dari sejumlah akademisi dan aktivis hukummenunjukkan adanya kecemasan bahwa hukum dapatmenjadi alat kekuasaan, bukan lagi sarana keadilan.Jika amnesti dan abolisi dipakai secara selektif danterkesan politis, maka prinsip due process of law danindependensi lembaga peradilan bisa terkikis. Hal inidapat memperburuk kepercayaan publik terhadappenegakan hukum di negeri ini.
Meski begitu, pemerintah beralasan bahwapengampunan ini merupakan bagian dari langkahrekonsiliasi nasional menjelang peringatan HariKemerdekaan. Alasan ini tentu tidak sepenuhnya salah.Dalam sejarah politik Indonesia maupun negara lain, pengampunan sering dijadikan sarana memperkuatpersatuan pasca-ketegangan politik. Namun perludiingat, rekonsiliasi tidak bisa dibangun denganmengorbankan prinsip keadilan. Stabilitas yang dibangun tanpa fondasi moral akan mudah goyah, dankepercayaan publik tidak akan terbangun darikompromi yang meragukan.
Dalam kerangka pembangunan hukum, amnestidan abolisi harus diposisikan sebagai langkah luarbiasa yang hanya digunakan dalam situasi sangatkhusus, dengan pertimbangan yang benar-benarmatang dan transparan. Presiden memang memiliki hakprerogatif, tetapi hak ini tidak boleh dijalankan secaramutlak. Ia harus tetap tunduk pada nilai-nilai moral danprinsip dasar negara hukum.
Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwapemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto danabolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah yang sah menurut konstitusi, sejauh dilakukan sesuaimekanisme yang telah diatur. Kendati demikian, sahsecara hukum bukan berarti bebas dari ruang evaluasipublik.
Masyarakat berhak untuk mengawasi danmemberikan kritik sebagai bentuk partisipasi dalammenjaga marwah hukum dan demokrasi. Dalam negarahukum yang sehat, kebijakan pengampunan seharusnyatidak menjadi instrumen kompromi politik atau sekadarsimbol belas kasihan dari kekuasaan.
Sebaliknya, hukum harus tetap berdiri teguh sebagai pelindungnilai keadilan dan kepentingan publik. Pada akhirnya, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukurdari formalitas prosedurnya, melainkan dari sejauhmana ia mampu menghadirkan keadilan yang nyatadan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.